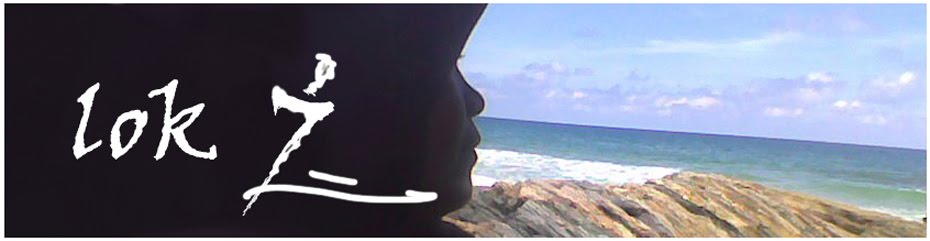Maman S Mahayana*
“Jiwa adalah cermin bening; tubuh adalah debu di atasnya…,”
begitulah pesan Jalaluddin Rumi ketika kita berhasrat hendak memperoleh
pencerahan dari Sang Maha Pencerah. Bersihkanlah debu atas tubuh, maka cermin
bening itu akan memancarkan cahaya-Nya. Sebuah pesan spiritual simbolik. Rumi secara
metaforis sekadar menorehkan risalah sufistiknya, semata-mata agar kita,
makhluk manusia dapat memperoleh kesadaran untuk selalu dapat mengendalikan
hawa nafsu yang berkaitan dengan kepuasan dan kenikmatan segala sesuatu yang
fisikal, yang badani, atau yang bersifat duniawi. Hanya dengan pengendalian
hawa nafsu itulah manusia akan dapat menangkap pantulan cermin bening itu:
cahaya Ilahi.
Banyak risalah sufistik Jalaluddin Rumi atau para penyair
sufi yang lain yang sebenarnya dapat menjadi bahan perenungan kita. Maka, tidak
perlu heran, ketika kita berjumpa dengan pesan-pesan sejenis, kita seperti
tidak dapat menghindar untuk tidak menghubungkannya dengan buah pikiran Rumi.
Meskipun begitu, boleh jadi Rumi sendiri sebenarnya tidak meniatkan ekspresi kesadaran
apokaliptiknya sebagai puisi. Ia sekadar mewartakan gejolak jiwanya yang paling
dalam sebagai bentuk pengagungannya pada Tuhan. Atau, itulah ekspresi kerinduan
dan cintanya pada Sang Khalik.
Dalam banyak kasus, ketika seseorang berhadapan dengan
sesuatu benda atau peristiwa atau apa pun yang membuatnya takjub, bergetar,
terpesona, atau bahkan sangat menakutkan, tanpa disadarinya, akan muncul begitu
saja, ekspresi puja-puji, atau permohonan agar mendapat perlindungan dan
pertolongan, doa keselamatan atau jampi-jampi penolak bala. Ekspresi itulah
yang dalam bahasa teologis disebut mysterium tremendum et fascinans, yaitu adanya misteri atau rahasia
yang menakjubkan—menakutkan—mempesona—dan seketika menariknya sekaligus pada
kesadaran transendensi. Tuhan atau Sang Penguasa jagat raya lalu menjadi objek
yang diharapkan bersedia turun tangan mengatasi semuanya, melakukan pertolongan
atau menjauhkan segala mara bencana.
-----------
-----------
*
Makalah “Temu Penyair Delapan Negara” diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh, di Banda Aceh, 15—17 Juli 2016.
* Pengajar Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
Dalam suasana seperti itu, bahasa terbaik
manusia, yang indah dan mempesona, yang mengandung bujuk-rayu atau yang menyimpan
daya magis, akan menjadi pilihan. Puisi dianggap paling mewakili ekspresi itu.
Maka, bahasa puisi kerap memanfaatkan kekuatan diksi (gaya bahasa), menciptakan
kesamaan bunyi atau rima, memainkan perulangan (repetisi), dan belakangan
membangun metafora atau personifikasi dan majas lain untuk menghidupkan
asosiasi pembaca atau pendengar. Dari sanalah puisi, seperti yang diyakini oleh
kaum romantik, dianggap menyampaikan suara kebenaran yang lahir dari kedalaman
hati, dari qalbu, dari sifat-sifat
Tuhan. Hati sebagai sumber yang menggerakkan suara
kebenaran dan kejujuran. Konon, manusia hidup lantaran roh bertahta dalam hati.
Roh itu pula yang menggerakkan hati. Adapun nurani
(Arab: nuroniy) bermakna bersifat
kecahayaan. Jadi, hati nurani sesungguhnya metafora untuk menunjukkan, bahwa di
sana ada cahaya, dan cahaya itu representasi Tuhan.
Oleh karena itu, pernyataan kaum
romantik, bahwa “Tuhan bertahta jauh dalam batin-jiwaku yang
megah,” tidak lain, merupakan bentuk hiperbolisme untuk
menegaskan bahwa suara hati nurani adalah suara Tuhan, dan puisi sebagai
ekspresi kata hati adalah suara kejujuran yang menyampaikan kebenaran, maka di
dalamnya memancar suara Tuhan. Itulah
keyakinan kaum romantik yang menempatkan kata atau suara hati sebagai
representasi Tuhan. Maka pernyataan kaum romantik: “Aku laksana Tuhan dalam pikiranku yang terdalam,” atau “Tuhan bertahta jauh dalam batin-jiwaku yang megah” dimaksudkan
sebagai aku sang pencipta kebenaran
menurut pikiranku, sebab suaraku adalah kejujuran sebagai representasi suara Tuhan.
***
Begitulah, membaca puisi-puisi Rosmiaty
Shaari, Melaka, sebagaimana yang terhimpun dalam antologi Daun nan Bercinta (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia (ITBM) dan Pena, 2016, xli + 90 halaman) dan puisi-puisi D Kemalawati,
Bayang Ibu (Banda Aceh: Lapena, 2016,
xix + 78 halaman), dalam sejumlah besar puisinya seperti memancarkan suara qalbu, suara kebenaran! Jika demikian,
apakah kedua penyair itu meluahkan suara qalbu,
suara kebenarannya sebagaimana yang dilakukan Jalaluddin Rumi atau para penyair
sufi? Jika tidak, bagaimana pula kedua penyair dari dua tradisi yang
berbeda—Melayu—Melaka dan Aceh—memperlihatkan adanya kesamaan ketika keduanya
berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan? Bagaimana pula kedua
penyair itu, dengan caranya masing-masing, mengungkapkan ketakjuban dan
keterpesonaannya ketika sebuah peristiwa diyakini sebagai bagian dari perkara
imanensi. Oleh karena itu, di dalamnya ada persoalan transendensi. Jika begitu,
di mana letak persamaan dan perbedaannya?
Membaca
puisi-puisi Rosmiaty Shaari dan D Kemalawati, dan coba membandingkannya, saya
seperti dihadapkan pada dua dunia yang berbeda, meski di sana-sini, dapat pula
dijumpai adanya sejumlah kesamaan. Adanya kesamaan itulah yang membawa kita
pada satu kesimpulan, bahwa perkara religiusitas dapat mempertemukan kedua
penyair itu pada satu sikap, yaitu cara ‘memandang’ Tuhan. Atau, menempatkan
Tuhan sebagai objek yang entah berada di mana, tetapi keduanya merasa perlu
untuk selalu menyapa dan mengingat-Nya, di mana pun dan dalam situasi apa pun.
Atau lagi, keduanya merasa perlu terus memelihara kesadarannya sebagai wujud
rasa syukur atas nikmat yang diterimanya. Lalu, puisi menjadi pilihan.
Dalam kajian sastra bandingan (comparative literature) memang dimungkinkan
membandingkan satu karya sastra dengan karya sastra lain, atau juga dengan
karya seni lain. Dan selalu, di sana, dalam kajian sastra bandingan itu, kita
akan berjumpa dengan persamaan ketika karya sastra itu mengungkapkan problem karakteristik
manusia: cinta, rindu, dendam, dosa, dan seterusnya yang semuanya berlaku
secara universal. Pada sisi yang lain, kita juga akan berjumpa dengan perbedaan
ketika persoalan kemanusiaan itu menyentuh warna lokal yang menyangkut tradisi
masyarakat dan budaya setempat. Selalu ada sesuatu yang khas, yang unik dalam
setiap kebudayaan masyarakat, yang tidak selalu terdapat pada kebudayaan
masyarakat lain. Di situlah, kajian sastra bandingan diperlukan sebagai salah
satu upaya memahami kebudayaan masyarakat lain. Dengan begitu, karya sastra
sebenarnya dapat digunakan sebagai pintu masuk memahami kebudayaan sebuah
bangsa.
Dalam usaha membandingkan sejumlah puisi
kedua penyair Rosmiaty Shaari dan D Kemalawati itu, tentu saja tidak semua
puisi yang terhimpun dalam antologi itu perlu dikaji seluruhnya. Cukuplah
beberapa puisi yang representatif memperlihatkan adanya persamaan tematik.
Meskipun demikian, gambaran umum tentang kedua antologi puisi itu, perlu kiranya
terlebih dahulu dipaparkan serba sedikit.
***
Antologi puisi Daun nan Bercinta (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku
Malaysia (ITBM) dan Pena, 2016, xli + 90 halaman) karya Rosmiaty Shaari, berisi
75 puisi yang secara tematik menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Kata
Pengantar Arbak Othman (xi—xliii) yang luas dan panjang lebar itu, jelas hendak
menegaskan posisi penyair dalam perkara hubungan aku—Tuhan, dan puisi-puisinya
seperti merepresentasikan hubungan vertikal, makhluk manusia dan Sang Pencipta.
Dikatakan Arbak Othman, “Semua ini menggambarkan dengan jelas konsep
hubungan manusia dengan Tuhan yang melalui ruang diri, menjadi objek rohaniah
yang akur dengan Perintah Ilahi: bermuhasabah diri, taat kepada ketetapan,
berharap kepada yang memiliki Kuasa Agung, bersikap tawaduk dan lemah lembut
kepada Pencipta Yang Maha Esa.” (hlm.
xliii). Meskipun kita (: pembaca) boleh tidak bersetuju atas pernyataan itu, setidak-tidaknya,
Kata Pengantar tersebut dapat digunakan sebagai bahan awal untuk melengkapi pemahaman
kita atas puisi-puisi Rosmiaty Shaari secara umum.
Dalam perkara tafsir atas puisi, pengalaman
dan pemahaman kita sering kali membawa kita punya pandangan dan makna lain.
Oleh karena itu, tidak terlalu bermasalah apabila penafsiran dan pemaknaan kita
atas sebuah puisi tidak sejalan dengan pandangan pembaca lain. Bagaimanapun
juga, sebuah teks puisi tidaklah terkungkung pada makna tekstual. Selalu ia
dapat dikaitkan dengan konteks sosio-budaya yang melahirkannya atau yang
menjadi harapan ideologis penyairnya. Lalu, berdasarkan kebebasan menafsir,
kita diberi peluang untuk coba menukik lebih dalam untuk mengungkapkan kekayaan
terpendam yang tersimpan pada teks puisi yang bersangkutan. Bukankah tafsir
pembaca itu juga sangat ditentukan oleh pengalaman masing-masing pembaca dalam
memahami dan memaknai sebuah teks?
Sementara itu, antologi puisi D
Kemalawati, Bayang Ibu (Banda Aceh:
Lapena, 2016, xix + 78 halaman) berisi 61 puisi dengan sebuah pengantar yang
berupa cerpen berjudul “Bayang Ibu (Di Depan Bayang Masa Lalu).” Tentu penyair
punya maksud lain atas pemuatan cerpen itu. Tidak serta-merta penyair
menempatkan cerpen sebagai semacam pengantar antologi puisinya, tanpa tujuan.
Niscaya ada pesan tertentu yang hendak disampaikannya.
Dan benar! Cerpen itu laksana pintu
masuk yang menyimpan trauma sejarah. Kemalawati tak menyinggung keagungan masa
lalu kesultanan Aceh yang reputasional. Tak juga menyentuh heroisme secara luas
perlawanan masyarakat Aceh pada kolonialisme Belanda, meski di sana ada puisi
“Tentang Teuku Umar” dan puisi yang membandingkan ketokohan “Kartini dan Cut
Nya Dien.” Secara keseluruhan Kemalawati coba mewartakan tragedi yang menimpa
masyarakat di sekeliling sebagai bagian dari pengalaman individualnya. Namun, belum
usai dengan tragedi itu, yang dikatakannya: “Betapa celakanya kampung ini, keluh anak-anak muda yang mengeram bara”
tiba-tiba alam memperingatkan dengan cara yang lain. Tsunami mahadahsyat menyisakan
mayat-mayat dan duka lara tak terperi!
Begitulah, dunia Aceh adalah kisah masa
lalu yang agung dan reputasional, yang heroik dan penuh perlawanan, yang
mengeram bara dan kecurigaan, dan yang masyarakatnya dengan segala
kesabarannya, mengumpulkan kembali puing-puing kehidupan setelah diterjang
tsunami!
Antologi puisi D Kemalawati, Bayang Ibu, sesungguhnya menyimpan
peristiwa-peristiwa besar itu. Segalanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari kehidupan masyarakat Aceh, dan Kemalawati menyadari tanggung jawab
kepenyairannya. Maka, puisi-puisinya menampilkan tema-tema yang beragam: dunia
Aceh yang penuh gejolak. Meskipun demikian, dalam konteks membandingkan
puisi-puisi Rosmiaty Shaari dengan puisi-puisi D Kemalawati, saya terpaksa lebih
memusatkan perhatian pada teks puisi yang secara tematis memperlihatkan adanya
sejumlah kesamaan. Maka, tak terhindarkan, saya memilih beberapa puisi
Kemalawati yang senafas dengan puisi-puisi Rosmiaty Shaari: tema-tema religius.
Sedikitnya ada sekitar 10-an puisi
Kemalawati yang tampaknya sengaja mengangkat tema religius. Dengan demikian,
usaha membandingkan puisi-puisi Rosmiaty Shaary dan puisi-puisi D Kemalawati,
secara metodologis, tak terkesan dipaksakan.
Mari kita mulai!
***
Kecenderungan
yang sangat menonjol dari sejumlah besar puisi-puisi Rosmiaty Shaari adalah hasratnya
untuk ‘menyapa’ Tuhan, bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan-Nya, dan coba
selalu mengingat, bahwa alam jagat raya dengan segala isinya yang mewarnai
kehidupan manusia, tidak lain adalah sarana untuk memuja-Nya. Atau, segala
tanda-tanda alam itu, dihayatinya sebagai hasrat untuk membersihkan diri dari
segala dosa. Dalam konteks itu, hubungan manusia dan Tuhan berada secara
vertikal sebagai hamba dan Sang Penguasa jagat raya. Ada keberjarakan antara
aku dan Tuhan, antara subjek—aku yang disadarinya berada dalam kuasa
objek-Tuhan.
Kita tidak menemukan representasi
hubungan aku—Tuhan dalam puisi-puisi Rosmiaty Shaari sebagai aku yang rindu jumpa
Dia, Sang Khalik. Atau ‘aku’ yang tiada berdaya atas kuasa-Nya lalu berhasrat
lebur dalam pesona-Nya. Dikatakan Rumi, “Ada saat kupunya seribu hasrat. Namun,
dalam satu hasratku mengenal-Mu, luruh tanpa sisa semua selainnya.” Jadi,
ketika datang hasrat akan pertemuan dengan Tuhan, seketika hasrat itu seperti
‘menelan’ semua hasrat yang lain.[1]
Bagi Rosmiaty, keberadaan aku duniawi memberi
penyadaran sebagai aku individu, sebagai makhluk-Nya. Dengan demikian,
keberjarakan aku-individu dan Tuhan, tidak berada dalam posisi aku rindu Sang
Kekasih, sebagaimana dikatakan Amir Hamzah: “Satu kekasihku/Aku manusia/Rindu rasa/Rindu rupa// (“Padamu Jua”). Atau, aku-individu yang tak berdaya
dalam pesona-Nya. Jadilah sang aku tidak berada dalam: mangsa aku dalam cakarmu. Juga tidak berada dalam posisi “Tuhan, kita begitu dekat/sebagai api dengan panas/aku panas dalam
apimu// (Abdul Hadi WM).
Meskipun demikian, sebagai makhluk
ciptaan-Nya, manusia tidak dapat melepaskan diri dari pancaran kasih Tuhan.
Sebagai manusia yang menyadari segala kelemahan dan kedaifannya, ia berharap
juga dapat merengkuh sifat-sifat-Nya atau yang dikatakan Kemalawati: menjadi
kekasih-Mu. Perhatikan puisi Rosmiaty Shaari dan D Kemalawati berikut ini.
ROSMIATY SHAARI
CATATAN PENGHULU HARI
setiap
kali menguak pintu hari
adalah
kebajikan yang kita impi
namun
setiap kali kita menutup pintu hari
jejak
yang ditinggal
sering
menangisi
setelah
kaki yang melangkah pergi
sarat
lumpur daki duniawi ...
ya
... Rabb
bersihkanlah
hati kami
agar
kami sentiasa dapat
membersih
lumpur di kaki kami
aamiiin....
12 Julai 2012
D KEMALAWATI
TUNTUN AKU YA RABB
Entah
sampai hitungan ke berapa
kaki
ini masih melangkah
di
atas taburan bunga
atau
serpihan kaca
Duhai
Rabb,
aku
mencium wangi-Mu
dalam
sunyi jalan menuju
harap
cemasku
akankah
kau rangkul tubuhku
bila
bertemu
Duhai
Rabb
izinkan
aku menjadi kekasih-Mu
tuntun
langkahku hingga berhenti
dalam
pangkuan-Mu
Banda
Aceh, 2 April 2014
--------------
[1] Haidar Bagir, Belajar Hidup dari Rumi, Jakarta:
Mizania/noura, 2015, hlm. 85.
Tampak dalam kedua puisi itu, kedua
penyair merasa diri sebagai makhluk-Nya yang tak ingin salah langkah. Mereka
(masih) berkutat dalam hubungan vertikal: aku sebagai hamba-Nya. Maka, Rosmiaty
selalu berharap, setiap langkahnya adalah kebenaran sebagaimana yang menjadi
ketentuan-Nya. Begitulah, kehidupan keseharian manusia, sebagaimana yang
menjadi harapan aku lirik, seyogianya selalu diikuti dengan refleksi diri,
introspeksi, yang dikatakan Kemalawati sebagai: … melangkah/di atas taburan bunga/atau serpihan kaca/ Lalu, siapakah
yang dapat menentukan kebenaran itu, selain Tuhan? Pertanyaan itulah yang membawa aku lirik dalam
puisi Rosmiaty kerap disertai dengan kesadaran melakukan introspeksi: bersihkanlah hati kami/agar kami sentiasa dapat/ membersihkan
lumpur di kaki kami//
Tetapi, bagi Kemalawati,
persoalannya tidak berhenti sampai di sana. Ada tujuan yang yang lebih
subtansial, yaitu: izinkan aku menjadi
kekasih-Mu/tuntun langkahku hingga berhenti/ dalam pangkuan-Mu// Sebenarnya,
dalam banyak puisi yang menempatkan Tuhan sebagai Sang Kekasih, atau aku—engkau
sebagai pecinta dan sang kekasih, keberjarakan itu lesap dalam hasrat untuk
menyatu. Atau, seperti dikatakan Rumi, … menelan
hasrat yang lain. Maka, peliharalah cinta pada Sang Kekasih itu. Sebab,
seperti dikatakan Rumi lagi: “Pecinta dan kekasih, tidaklah baru bertemu di
akhir perjalanan. Mereka selalu bersama sepanjang perjalanan.” (Haidar Bagir,
2015: 215)
Begitulah, spirit kedua puisi itu
adalah menempatkan Tuhan sebagai sumber segala kebersihan. Maka, yang perlu
dilakukan adalah setiap saat membersihkan segala lumpur yang melekat. Bagaimana
mungkin ‘lumpur’ dapat menjadi bagian dari sumber segala kebersihan? Dengan
begitu, izinkan aku menjadi kekasih-Mu/
adalah hasrat aku lirik untuk menjadi pecinta. Nah, tampak di sini, baik
Rosmiaty, maupun Kemalawati, sesungguhnya mempunyai perasaan yang sama dalam
memandang Tuhan, yaitu menempatkan diri sebagai “dari mana dan akan ke mana
tujuan hidup manusia.” Lebih tegas lagi: dari Tuhan kembali ke Tuhan.
Dalam puisi “Jihad Badani” kembali
kesadaran diri aku lirik datang ketika realitas kehidupan tidaklah berlangsung
baik-baik saja. Manusia kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan yang saling
bertentangan: kebaikan atau keburukan, kebenaran atau kepalsuan, kekejaman atau
kasih sayang, cinta atau benci, dan seterusnya. Atas berbagai pilihan itulah manusia
berada dalam medan perang yang sesungguhnya. Menang atau kalah, bergantung atas
pilihannya. Itulah yang disebut jihad, yaitu perang melawan musuh yang tak
terlihat; perang menundukkan hawa nafsu dan keangkaramurkaan. Perang besar yang
bersifat fisikal, justru dimulai dari perang melawan hawa nafsu ini. Maka
memenangkan perang ini, berarti memenangkan segala perang yang bersifat fisikal
itu.
JIHAD BADANI
Allahu
Rabbi ...
titis
bening di subuh hening
rebah
ke pangkal rahim
menancap
bulan sakral
kekasih
di
dadaku
ada
darah memerintah
setiap
anggota menggelepar
mabuk
melihat merah
jihad
perang
nafsu-nafsi.
24
Ramadan 1433
“Jihad Badani” adalah kesadaran aku
lirik bahwa kehidupan keseharian dalam menentukan berbagai pilihan tidak lain
adalah ‘jihad’. Kekasih sebagai simbolisasi (sifat) Tuhan, lesap dalam jiwa
yang menggerakkan segala langkah perbuatan adalah pilihan yang mesti dijalankan
dalam perang melawan hawa nafsu. “Jihad Badani” adalah perang melawan musuh
yang tak terlihat. Perang batin yang terjadi dalam diri sendiri, yaitu perang
melawan hawa nafsu. Dalam dua larik terakhir puisi itu dikatakan: jihad perang/nafsu-nafsi// yang berarti bahwa perang melawan hawa nafsu adalah
peristiwa jihad. Rumi mengingatkannya begini: “Hawa nafsumu adalah induk segala berhala …”[2]
Maka, hawa nafsu bagi Rumi adalah neraka atau bagian dari neraka yang
hakikatnya tidak lain adalah setan. Dengan demikian, perang melawan hawa nafsu,
sesungguhnya adalah perang melawan setan.
Peristiwa perang simbolik ini juga
diangkat Kemalawati dalam puisinya “Batu-Batu Kerikil dari Muzdalifaf.” Dalam
puisi itu, penyair tidak menarik peristiwa perang simbolik itu sebagai
peristiwa batin, melainkan potret suasana aku lirik memasuki pusaran peristiwa
yang membuatnya hanyut, lesap, luruh-lebur di antara kesadaran dan
ketidaksadaran. Barangkali juga perisiwa itu bagian dari suasana trance, mabuk dalam kenikmatan perang
melawan setan. Perhatikan penciptaan suasana peristiwa yang digambarkan
Kemalawati.
BATU-BATU KERIKIL DARI MUZDALIFAH
Batu-batu
kerikil di lautan pasir Muzdalifah
seperti
bintang-bintang dalam balutan awan
tak
terhitung jumlahnya
Kami,
lelaki berselempang ihram
perempuan-perempuan
menutup seluruh badan
dalam
ihram dalam pantang
datang
bergelombang
mengais-ngais
pasir memilih kerikil
dengan
zikir
dengan
zikir
Lewat
tengah malam
para
pejalan yang tangguh
mengayuh
badan di remang bayang
jutaan
yang lain menunggu di tepi jalan
menunggu
giliran angkutan
semua
menuju Mina
merapat
ke Jamarat
Wahai
kabir, wustha dan shoghir
berkumpullah
kalian di Ula, Wustha dan Aqabah
terus
goda manusia, terus tipu hamba Allah
Kami
datang bersama kerikil di tangan
menyusuri
jalan berliku, terowongan-terowongan panjang
tangga
tinggi menjulang, tebing curam
Untuk
melemparmu
dengan
jutaan kerikil
dengan
seruan takbir
Batu-batu
kerikil di sela hamparan pasir Muzdalifah
seperti
dipilih Ibrahim, kami pilih melempar kabir di Ula
seperti
dipilih Hajar, kami pilih melempar
Wustha
di antara Ula dan Aqabah
seperti
yang dipilih keduanya, para kekasih Allah
Kami
pilih untuk melempar ketiganya
Kabir,
wustha dan shoghir di Aqabah
Batu-batu
kerikil berselimut pasir dari Muzdalifah
cahaya
kaliankah yang kami saksikan
membusur
dari kolam menembus awan
terang
melebihi bintang-bintang
Wahai
Yang Maha Penerang
Kami
penuhi panggilan-Mu
Labbaik
Allahuma labbaik
Labbaik
Allahuma labbaik.
Muzdalifah-Banda
Aceh, 2012-2013
-----------------
[1] Reynold A. Nicholson, Jalaluddin Rumi: Ajaran dan Pengalaman Sufi,
terj. Sutardji Calzoum Bachri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 36.
Mengingat yang dilakukan Kemalawati
adalah usaha mengangkat suasana peristiwa, maka citraan penglihatan dalam puisi
itu terasa begitu kuat. Kita laksana dibawa ikut masuk pada pusaran orang-orang
dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya, kemudian ikut bergerak, bergelombang
menuju satu tujuan sambil mengumandangkan gemuruh takbir dan puja-puji.
Begitulah, Rosmiaty yang dalam
kesenyapannya mewartakan perang batin, perang melawan hawa nafsu, sesungguhnya
melambangkan perang melawan “induk segala berhala”. Adapun Kemalawati
mengangkatnya tidak dalam kesenyapan, melainkan dengan penciptaan suasana yang
penuh dengan kegemuruhan dan gelombang lautan manusia yang bergerak menuju satu
titik yang sama: melawan setan!
***
Sejumlah besar puisi Rosmiaty,
seperti telah disebutkan, cenderung menariknya sebagai peristiwa individual
dalam kehidupan keseharian yang kerap menumbuhkan kesadaran tentang keberadaan
Tuhan. Atau, setidak-tidaknya, dari peristiwa-peristiwa yang tampaknya
biasa-biasa saja, selalu ada isyarat lain yang menegaskan hubungan manusia dan
Tuhan. Periksa saja puisinya yang berjudul “Catatan Sehelai Daun 1” atau
“Percakapan Waktu Pagi” berikut ini
CATATAN SEHELAI DAUN 1
pabila
ditumbuhkan sebatang pohon
sulur
pertamanya mengakar ke bumi
tunasnya
memucuk ke langit
kian
membesar berdaun hijau
subur
sebelum
gugurnya sehelai daun
yang
hijau atau yang kuning
akhirnya
tetap dikuras musim
tetap
akan mengering
dan
seperti sepohon syajar
entah
esok atau lusa
daunmu
akan gugur
hijau
atau kuning
tetap
akan gugur – maka
kembalilah
kamu
ke
asalmu
sekepal
tanah ...
23
November 2011
“Catatan Sehelai Daun 1” adalah
kisah sederhana tentang biografi daun. Dalam puisi ini, Rosmiaty seperti enteng
saja, tanpa beban, berkisah tentang perjalanan hidup daun. Tetapi kemudian
kisah tentang daun itu tidak lain adalah isyarat bagi kita, manusia. Sebuah
analogi tentang perjalanan hidup manusia: kembalilah
kamu/ke asalmu/sekepal tanah// Dalam konteks yang lebih
luas, Rosmiaty mengingatkan, bahwa berbagai peristiwa remeh-temeh yang berada
di sekeliling kita, yang setiap hari kita jumpai, di sebaliknya ada tanda-tanda
isyarat keberadaan Tuhan. Peristiwa seperti itu, secara simbolik dikatakan Rumi
sebagai berikut: “Kau berjalan ke sana ke
mari/menunggang kudamu/dan bertanya kepada setiap orang/“Mana kudaku?”//
Permainan Rosmiaty adalah dunia
persekitaran. Ia lalu menariknya menjadi bahan renungan. Dari sana, ia
mengambalikannya lagi sebagai usaha memberi penyadaran bagi kita. Lihat saja
puisinya yang lain yang berjudul “Percakapan Waktu Pagi,” “Di Retak Batu,”
“Khabar kepada Kawan,” “Lapar,” atau
“Fakir” –sekadar menyebut beberapa—adalah kisah sederhana, peristiwa
keseharian, dan tak penting. Tetapi di balik itu, ada kisah besar tentang
hubungan manusia dan Tuhan, tentang kesadaran manusia dalam menyikapi hidup
ini, dan segalanya terpulang pada sensitivitas qalbu, sebagai kata hati, suara
kebenaran yang di sana terpancar pendar cahaya Ilahi. Periksa saja puisinya
yang berjudul “Lapar” berikut ini.
LAPAR
lapar
itu benang sutera
yang
berkepompong di dalam dada sekian lama
lalu,
menjadi sekuntum ovarium
yang
menitiskan madu
ke
dalam dendrobium
sepasang
lebah pun berlegar
hinggap
ke dalam laparmu
menyedut
manis madumu
ketika
laparmu meronta
menikmati
lazatnya cahaya....
Lapar yang dikataknnya sebagai
benang sutera yang berkepompong … dan seterusnya pada akhirnya sampai juga pada
hakikat lezatnya cahaya. Sebuah analogi yang cantik, meski sederhana. Namun,
tokh puisi itu tidak meninggalkan kedalaman maknanya, bahwa segalanya tidak
terlepas dari cahaya Ilahi.
Begitu juga puisinya yang berjudul
“Fakir” berikut ini.
FAKIR
berilah
aku sedikit cinta
dari
secarik roti yang kaumakan
dan
seteguk rindu
dari
secangkir madu yang kautelan
di
telapak tangan
ada
doa kusisipkan.
Dalam sejumlah besar puisinya,
Rosmiaty Shaari menawarkan spirit religiusnya mengalir begitu saja, tanpa beban,
tanpa perlu berteriak menyampaikan ayat-ayat Quran atau khotbah. Apa saja
benda-benda alam atau peristiwa keseharian biasa, dapat menjadi peringatan luar
biasa ketika Rosmiaty menariknya sebagai perenungan batin yang lalu disadari,
bahwa segalanya tidak terlepas dari cahaya Ilahi bagi umat manusia. Kesadaran
itulah yang kemudian dipancarkan kembali menjadi tanda-tanda atau isyarat alam,
bahwa di sana tersembunyi cahaya Ilahi.
Puisi-puisi D Kemalawati, meski
dengan pesan yang sama, yaitu konteks hubungan manusia—Tuhan, ia menyampaikannya
dengan cara yang lain. Sebagaimana puisinya “Batu-Batu Kerikil dari
Muzdalifaf,” yang sudah disinggung tadi, dalam puisi yang berjudul “Aku
Melingkar Terbakar” penyair lebih menekankan pada suasana peristiwa. Maka,
gambaran ribuan manusia yang mengelilingi Kabah, gelombang gema takbir atau
doa-doa memuja kebesaran-Nya atau entah apa lagi, mewartakan kemahabesaran-Nya
yang tak berhingga. Kita –pembaca—seolah-olah dibetot pada suasana kedahsyatan
peristiwa itu. Kembali, kita dapat membayangkan, betapa lautan manusia di sana
mengalami trance, mabuk, hanyut,
luluh, lebur dalam gelombang manusia dalam kenikmatan religius yang tak
terperikan. Manusia dari berbagai bangsa dan budaya dipersatukan oleh keimanan
yang sama.
AKU MELINGKAR TERBAKAR
Aku
di sini
di
tempat para penabuh
meriuh-rendahkan
tabuhannya
rindu
nyanyian padang lengang
aku
dan Tuhan
Para
penabuh melingkar-lingkar tubuh
berbalut
hitam, batu hitam, mata hitam
air
mengalir, putih, jernih
dalam
haus zam-zam
sedepa
maqam
aku
dan Tuhan
aku
dan Tuhan
Naik
turun bukit
tetabuhan
himpit
kanal-kanal
beriak
diri
tak bertali tak kendali
aku
dan Tuhan
Mereka
melingkar-lingkar
mendayung
perahu jangkar
para
penabuh yang terbakar
aku
ikuti mereka
menabuh
dan terbakar
aku
dan Tuhan
Makkah-Banda
Aceh, 2012-2013
Cermatilah, betapa kuatnya
larik-larik ini: Mereka
melingkar-lingkar/mendayung perahu jangkar/para penabuh yang terbakar/aku ikuti
mereka/menabuh dan terbakar/aku dan Tuhan// Begitulah, religiusitas
Kemalawati cenderung tidak sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai
bagian dari kehidupan masyarakat atau orang-orang yang berada di sekitarnya.
Jadi, aku lirik lesap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suasana peristiwa.
Periksa lagi, misalnya, puisinya yang
berjudul “Di Itaewon” yang mengangkat pengalamannya memasuki rumah Tuhan di
sebuah bukit yang dikepung tempat-tempat hiburan malam. Perjalanan menuju ke
masjid itu memang melewati jalan mendaki, seperti dikatakannya: Ini pendakian yang tak seberapa/namun tangga
berdinding batu seolah berkata/engahmu seolah pertanda belum terbiasa/menuju
ketinggian jiwa/para pencari ridha …
Selengkapnya simaklah puisinya yang
berjudul “Di Itaewon” berikut ini:
DI ITAEWON
Ini
pendakian yang tak seberapa
namun
tangga berdinding batu seolah berkata
engahmu
adalah pertanda belum terbiasa
menuju
ketinggian jiwa
para
pencari ridha
Kubasuh
muka
kuredakan
debar di dada
kudaki
lagi tangga dalam kamar samar cahaya
hingga
ruang lengang di lantai dua
sayup-sayup
kudengar seruan itu
mengalun
dari puncak menara
sujudku
dipenuhi airmata
Di
Itaewon, kukirim doa kepada
perempuan
muda sipit berkulit terang
yang
terbata-bata memadankan kata
kutahu
dia tak mencari pahala
ketika
menawarkan jasa menuju rumah-Nya
Mesjid
Itaewon, Seoul, 4 Juni 2012
Meski dalam puisi itu, Kemalawati
mengangkat pengalaman individual, ia menariknya sebagai bagian dari kehidupan
sosial. Maka, di sana dikatakan: perempuan
muda sipit berkulit terang … yang menawarkan jasa menunju rumah-Nya//
***
Membaca puisi-puisi Rosmiaty Shaari
dan D Kemalawati—khusus mengenai puisi-puisi religiusnya—kita seperti disuguhi
berbagai cara pandang dalam menyapa Tuhan. Meskipun begitu, dalam puisi kedua
penyair itu, kita tetap menemukan spirit yang sama, keimanan yang sama, dan
jiwa yang sama. Jadi, benarlah seperti yang dikatakan Rumi: “Orang-orang Mukmin
itu banyak, namun Iman itu hanya satu; tubuh mereka itu beraneka ragam, namun
jiwa mereka hanya satu.”[3]
* Makalah “Temu Penyair Delapan
Negara” diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Kuta Alam, Banda
Aceh, di Banda Aceh, 15—17 Juli 2016.
*
Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
[1] Haidar Bagir, Belajar Hidup dari Rumi, Jakarta:
Mizania/noura, 2015, hlm. 85.
[2] Reynold A. Nicholson, Jalaluddin Rumi: Ajaran dan Pengalaman Sufi,
terj. Sutardji Calzoum Bachri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 36.
[3] Reynold A. Nicholson, Jalaluddin Rumi: Ajaran dan Pengalaman Sufi,
terj. Sutardji Calzoum Bachri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 26.
-----------------------------------
[1]
Reynold A. Nicholson, Jalaluddin Rumi: Ajaran dan Pengalaman Sufi,
terj. Sutardji Calzoum Bachri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 26.